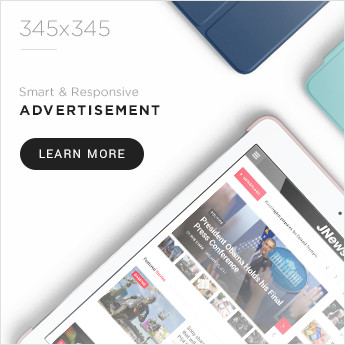Oleh: Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah UNIIB
OPINI (SuaraIndonesia.net)–Kepemimpinan sering kali dinilai dari hasil konkret atau tampak nyata seperti angka kemiskinan yang turun, kualitas layanan publik yang naik, atau jumlah investasi yang masuk. Tetapi ada satu sisi lain yang tak kalah penting, yaitu kepemimpinan simbolik yang mampu menyentuh emosi dan penilaian publik. Di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani menunjukkan sisi ini melalui sejumlah gestur yang tampak sederhana, tetapi mengisyaratkan makna tersendiri. Seperti yang baru-baru ini ditampilkan, beliau memilih naik ojek online (ojol) untuk berangkat ke kantor, dan kemarin melantik Sekretaris Daerah (Sekda) di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Sekilas, tindakan ini mungkin dianggap sebagian orang hanya sekadar pencitraan. Tetapi bila ditinjau dari konsep warm glow leadership, justru kita bisa membaca pesan moral yang berharga dan strategis. Teori warm glow pertama kali diperkenalkan oleh James Andreoni (1990). Intinya, seseorang merasa hangat, bahagia, atau puas secara batin ketika melakukan kebaikan atau memberi kontribusi, bukan hanya karena hasil manfaat publiknya, melainkan juga karena rasa senang dari tindakan itu sendiri.
Banyak studi kemudian memperluas gagasan ini. Bodner dan Prelec (2003), misalnya, menekankan bahwa memberi atau berbuat baik juga merupakan bentuk self-signaling: ketika seseorang bertindak altruistik, ia sekaligus mengirimkan pesan positif kepada dirinya dan orang lain tentang siapa dirinya, nilai moralnya, dan kepeduliannya. Dalam politik, self-signaling ini bisa tampil dalam gestur sederhana namun penuh makna—seperti naik ojol atau memilih TPS3R sebagai lokasi pelantikan pejabat.
Momentum pelantikan Sekda di TPS3R setidaknya memiliki tiga pesan warm glow leadership yang dapat kita tangkap. Pertama, prestise (Harbaugh, 1998). Seorang pemimpin memperoleh pengakuan karena berani keluar dari jalur formalitas. Pelantikan tidak lagi sekadar seremoni di ruangan ber-AC, tetapi justru di lokasi yang dekat dengan realitas keseharian masyarakat. Prestise yang dibangun bukan prestise kekuasaan, melainkan prestise moral.
Kedua, ada pesan pengakuan sosial (Hollander, 1990; Rege & Telle, 2004). Dengan membawa birokrasi ke TPS3R, Bupati seolah ingin berkata: “Ini loh, masalah yang dihadapi rakyat kita, mari kita sikapi bersama.” Dan mendorong publik merespons dengan rasa kedekatan, karena simbol itu menunjukkan kepemimpinan yang hadir, bukan berjarak.
Ketiga, tindakan itu menampilkan norma moral yang diinternalisasi (Nyborg et al., 2006). Ada keyakinan kuat bahwa birokrasi tidak boleh asing dengan problem rakyat, bahkan harus berdiri di garis depan. Pelantikan di TPS3R menyiratkan pesan bahwa masalah sampah—sering dianggap sepele—justru bagian penting dari agenda pelayanan publik.
Dari sini, kritik bahwa tindakan tersebut hanyalah gimik politik terasa kurang tepat. Memang, dalam politik selalu ada ruang bagi tafsir dan perdebatan. Namun, justru yang lebih penting adalah bagaimana simbol-simbol ini memberi arah baru, yaitu birokrasi yang inklusif, kepemimpinan yang berani keluar dari pakem, serta politik yang mengedepankan kehangatan, bukan sekadar angka dan formalitas.
Tentu, tetap ada ruang saran konstruktif. Kepemimpinan simbolik perlu ditopang dengan kebijakan nyata—misalnya memastikan bahwa TPS3R benar-benar berfungsi optimal, didukung anggaran yang cukup, serta melibatkan partisipasi warga. Dengan begitu, simbol yang tampak tidak berhenti sebagai gestur, tetapi menjadi penggerak perubahan struktural, merangkul, dan menyalakan semangat kebersamaan. Politik kehangatan ini menunjukkan bahwa sentuhan simbolik bisa menjadi energi yang meneguhkan kepercayaan publik. (***)